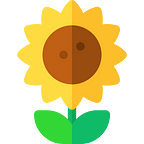Kalau ada satu konsep yang paling misleading pada masa ini, maka konsep tersebut adalah kompetisi. The case against competition, sebenarnya judul tulisan ini diambil dari bukunya Alfie Kohn yang judulnya “No Contest: The Case Against Competition”. Sebenarnya beliau secara spesifik membahas kompetisi di dalam konteks pendidikan atau lebih spesifiknya lagi sekolah. Tetapi, yang aku temukan sesungguhnya lebih dari itu — competition fails in many contexts of human lives, especially in relationship.
Alfie Kohn dalam sebuah lecture-nya mendefinisikan kompetisi secara singkat. “I win only if you fail.” Seseorang hanya bisa menang, berada di atas, kalau orang lain kalah atau gagal. Dan belief ini adalah belief yang secara nggak sadar menjadi konsep yang dipercaya benar bagi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu dijadikan kompetisi, dan hal tersebut sayangnya dinormalisasi, terutama dalam hubungan antar manusia.
Dalam pernikahan, banyak masalah yang terjadi itu akarnya kompetisi. Adu menang. Suami nggak mau kalah dari istri, istri nggak mau kalah dari suami. Merasa bahwa pasangannya adalah saingan. Suami tidak suka kalau istrinya benar dalam sesuatu karena terasa lebih cerdas dan mengalahkan dia. Istri tidak suka kalau suaminya mengatur dan membuat keputusan, karena merasa seperti lebih rendah dari suami.
Dua-duanya ingin merasa “paling” dalam hubungan. “Aku udah ngasih ini itu buat kamu, kamu ngapain?” Istri ingin merasa paling berjasa karena sudah mengorbankan segala hal dari dirinya dan susah payah mengurus anak. Suami ingin merasa paling berjasa karena sudah banting tulang menghidupi anak-anaknya. Merasa paling berjasa dengan hubungan, merasa paling berjasa dalam keluarga. Perempuan biasanya merasa paling sayang sama pasangannya, dan laki-laki merasa paling bekerja untuk pasangannya. Bahkan, biasanya juga ingin paling disayang oleh anak.
Kalau sudah merasa paling, seseorang akan sulit hold accountable terhadap apa yang terjadi dalam hubungannya. Kalau ada yang salah, mode blaming-lah yang terjadi: yang disalah-salahin adalah pasangannya. Bukan mutual understanding yang ingin dicapai. Tujuannya hanya untuk menang dan mengalahkan atau mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Di dalam sebuah hubungan, menjadi orang yang “paling” itu tidak penting. Yang seharusnya dilakukan adalah bekerja sama, saling melengkapi, dan saling memahami. Your spouse is not your rival. Note that.
Dalam parenting, kompetisi juga diterapkan. Pernah dengar konsep sibling rivalry atau persaingan antar saudara? Tadinya, aku kira itu konsep yang wajar dan dialami oleh semua anak, sampai kemudian aku yakin bahwa persaingan antar saudara bisa dihindari. Ya, bisa dihindari, jika orangtua berusaha adil dan tidak mengadu anak-anaknya. Masalahnya, ini tidak terjadi.
Anak-anak diadu dengan cara yang orang-orang pikir wajar. Misalnya: “kok kamu nangis, kakak aja pinter tuh nggak nangis” “masa kamu kalah sama adikmu, adik aja udah bisa makan sendiri” “kalau kamu nggak makan, ibu sayangnya sama adik aja deh, kamu nggak usah disayang”. Secara nggak sadar, orangtua ketika melakukan hal ini sedang mengadu anak-anaknya.
Aku baru tahu konsep yang namanya parental favoritism dari Mba Sisi, psikolog klinik Rainbow Castle. Parental favoritism adalah keadaan di mana orangtua punya anak favorit di antara anak-anaknya. Mungkin memang wajar, tapi yang tidak wajar adalah orangtua menunjukkan siapa yang paling ia sukai di antara anak-anaknya. Dengan membanding-bandingkan, dengan memberikan perlakuan khusus bagi anak yang paling ia sukai, dengan menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak yang paling ia sukai. Biasanya hal-hal ini dilakukan terang-terangan.
Orangtua memberlakukan kompetisi di antara anak-anaknya, tapi mereka bingung kenapa anak-anaknya sering bertengkar sama saudaranya. Tidak bisa bersosialisasi dengan baik ketika bermain bersama teman sebayanya. Dan bahkan anak-anaknya tidak mencintainya sebagaimana seharusnya. Padahal orangtua sendiri yang mengadu anak-anaknya.
Padahal tanpa perlu diadupun, anak-anak sudah memperebutkan kasih sayang orang dewasa yang mengasuhnya. Ketika aku mengajar anak-anakku di TK, mereka saja udah pengen paling dapat perhatian dariku. Nah, gimana kalau ditambah aku banding-bandingkan mereka dengan satu sama lain?
Selain mengadu anak-anaknya, dalam parenting, orangtua juga berkompetisi dengan anaknya sendiri. Tidak suka kalau anaknya punya pendapat yang benar. Tidak mau minta maaf kalau dirinya salah. Tidak bersedia jika anaknya memiliki pemikiran dan keinginan tersendiri. Hal seperti ini common sekali terutama dalam pengasuhan anak remaja. Intinya adu menang saja, bukan berusaha memahami, mencari kesepakatan, bekerjasama, dan berusaha belajar dari satu sama lain.
Kompetisi juga bisa terjadi di konteks lain seperti hubungan pertemanan. Biasanya orang yang menganggap temannya ini saingan tidak suka kalau temannya lebih baik dan mendapat kebaikan. Sering membanding-bandingkan dirinya dengan temannya. Tentu saja tidak nyaman berkompetisi dalam pertemanan.
Dalam hubungan relasi kerja, mungkin kompetisi terasa wajar. Tapi dalam kerja tim, tidak semua kompetisi bisa menjadi kompetisi yang sehat. Pemimpin adu menang sama bawahannya, bawahannya saling sikut-sikutan satu sama lain. Kerasanya wajar, padahal tidak sehat.
Competition doesn’t work in a relationship. Believe me.
Ketika kita sadar bahwa tidak semua hal harus diadu, perlahan-lahan kita sadar bahwa kompetisi tidak bekerja dalam hubungan. Kompetisi memutus koneksi, rasa kasih sayang yang genuine, dan rasa ingin memahami satu sama lain.
Kita itu sedang berada dalam hubungan, bukan lagi lomba 17-an.